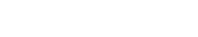56. RENCANA
56. RENCANA
pelanggan-pelanggan Mas Sardi. Beberapa hal tidak menyenangkan mulai ku alami. Aku memang
sudah terbiasa dengan dunia kerja. Tapi tetap saja dilecehkan saangatlah tidak menyenangkan.
Memang tidak sampai jauh hingga tindakan senonoh namun berupa ucapan-ucapan yang terkadang
terlewat nakal dan merendahkan.
Hal-hal seperti ajakan jalan-jalan dalam tanda kutip tentu saja makna jalan-jalan di sini bukan
sekedar jalan-jalan. Aku sudah hafal akan hal itu. Dulu aku pernah bekerja di sebuah restoran di
Jogjakarta. Aku bahkan mengalami hal yang lebih parah dari sekedar kata-kata. Terkadang sopir-
sopir yang mampir untuk makan itu pura-pura menabrak pelayan wanita hanya untuk menyentuh
bagian tertentu dari tubuh pelayan. Dan saat ini tidak ada hukum yang menyalahkannya.
Dari pengalaman-pengalaman mengerikan itu sekarang aku jadi muak dengan para hidung belang
itu. Sehingga sebelum aku menjadi santapan mereka lebih baik aku di cap sebagai gadis galak atau
judes saja.
Hari ini aku bertugas menimbang sawit yang baru datang. Aku mulai mengerti tugas Mas Sardi satu
persatu. Kadang Mas Sardi duduk mengawasiku. Namun kali ini Ia tidak terlihat. Mungkin ada di
belakang rumah karena Mba Ranti bilang buah sukun di belakang rumah sudah saatnya panen.
Oh ya, Santo ternyata hari ini melSimbokrkan diri. Aku sempat melihat dia minta ijin pada Mas Sardi tadi.
Anehnya sejak meminta ijin itu Santo malah menemani aku yang sedang bekerja. Terkadang dia
membantu karyawan memindahkan sawit. Bukankah percuma dia minta libur? Tapi kebetulan sekali
jadi aku bisa punya teman bicara.
Santo duduk di bangku semen sambil sesekali menyesap kopinya. Aku tahu Ia satu-satunya yang
melihat kejadian demi kejadian yang membuatku risih sejak pagi. Ada saja tingkah laku supir-supir
itu meski aku yakin sebagian pasti sudah beristri.
Kali ini supir truknya bernama Sigit. Atau biasa di panggil bang sigit. Ia sudah beristri dan punya dua
anak. Disini Ia merantau tanpa istrinya. Istrinya berada di Medan. Ia pernah bilang sesekali
membawa istrinya ke sini. Namun istrinya tidak pernah betah tinggal di sini. Sehingga mereka
terpaksa berpisah.
Bang sigit ini hampir tiap hari ke sini. Karena lahan sawit majikannya cukup luas. Ia beberapa kali
mengajakku keluar. Tapi aku menolaknya. Waktu pertama kali datang dia juga terus mencuri
pandang kepadaku. Dan itu berlanjut dengan rayuan-rayuan dan ajakan-ajakan. Meski ku tolak
berulang kali namun Ia tetap gigih. Yang lebih menyebalkan lagi adalah Ia tidak pernah
melakukannya di depan Mas Sardi.
Aku mengepalkan tanganku karena Bang sigit terus saja merengek. Ia benar-benar tidak
menghiraukan kerisihanku. Ketika aku menoleh kepadanya lalu melotot dan hendak marah padanya,
Santo menenggor tubuhnya. Sampai Bang sigit hampir terhuyung.
Bang Sigit sudah merah mukanya. Ia sudah bersiap mengumpat namun melihat Santo yang membawa
ganco Ia tidak jadi marah. Sementara Santo berhenti di depan kami. Dengan ganconya yang Ia
senderkan di bahu Ia lalu menoleh ke arah bang sigit dengan tatapan sini.
"Oi bang, minggirlah sikit. Kau bisa kena sawit kalau terlalu dekat." Ujar Santo dengan logat
menyerupai orang batak. Sontak membuat karyawan yang lain menoleh ke arah bosnya.
Bang sigit pun mengacungkan jempol kepada Santo dan mundur. Ia lalu duduk di bangku dan
menyesap kopinya.
Aku tersenyum ke arah Santo. Lalu memberinya jempol. Santo melanjutkan jalannya dan membantu
karyawan untuk memindahkan sawit. Sementara aku tetap di posisiku dengan membawa buku
catatan timbangan.
Akhirnya sore pun tiba. Aku duduk di bangku. Santo duduk disisiku. Ia nyemil sisa makanan yang
menjadi suguhan. Aku memutar punggungku ke kanan dan kiri. Terdengar bunyi khas grmertak
tulang-tulang.
"Pegel Nti?." Tanya Santo padahal jawabannya sudah pasti iya.
"Enggak." Ucapku yang sudah pasti bohong.
"Hmmm bohong."
"Kamu ini aneh Di. Sudah tahu pegel. Pake nanya. Kayak mau mijitin aja."
"Lah emang boleh?"
"Nih...boleh.." Aku memberikan kepal.ke wajah Santo yang mulutnya sedang penuh dengan singkong
goreng.
"Orang ngerokin aja pernah. Kalau cuma mijitin mah enteng..." Bisik Santo ke telingaku.
"Santo!." Akhirnya sebuah cubitan berhasil mendarat di paha Santo yang kekar. Dia mengaduh kesakitan
dan mengusapnya berkali-kali.
"Sakit Nti....kamu pikir ini gedebog apa." Ujar Santo sambil meringis.
"Bodo amat. Rasain tuh." Ucapku santai.
"Hobi kok nyubit."
Aku menjulurkan lidahku padanya. Lalu memasukkan sepotong singkong ke mulutku.
"Kamu betah di sini Nti?" Tanya Santo tiba-tiba. Membuatku berhenti mengunyah.
Aku tidak menjawab pertanyaannya. Santo adalah orang pertama yang sadar kondisiku saat ini.
"Kamu pasti risih sama supir-supir tadi. Sudah ngomong sama kakakmu? Atau simbokmu?" tanya Santo
lagi.
Aku hanya menggeleng. Lalu kutelan singkongku dan meminum air digelas yang tadi ku tuang.
"Kakakku hanya menganggap itu guyon. Santokku menganggap aku berlebihan dan anti laki-laki.
Mereka tidak menganggap ini serius." Jelasku pada Santo.
Santo hanya mengangguk-angguk menandakan paham dengan situasiku.
"Mungkin karena selama ini anaknya laki-laki jadi kurang paham bagaimana harus bersikap untuk
anak perempuan" Ujar Santo berusaha bijak.
"Ah tidak juga. Satu-satunya yang menganggapku emas adalah almarhum bapakku."
"Lalu apa rencanamu selanjutnya.?" Tanya Santo.
"Aku tidak berencana lama di sini Di. Mas ku itu tidak akan membiarkanku hidup bebas. Terlalu
banyak aturan." Jawabku. Santo hanya mantuk-mantuk mendengarnya.
"Kalau kamu San?." Tanyaku padanya.
"Aku? Kenapa?"
"Ya rencanamu gimana?" Tanyaku.
"Mmmm.." Santo tampak berpikir dengan jawabannya. Matanya jauh memandang awang-awang.
"Aku tidak punya rencana spesifik Nti." Jawabnya membuat alisku bertaut.
Aku hanya mantuk-mantuk. Tidak mau terlalu dalam bertanya.
"Kok gak tanya kenapa Nti?" Tanyanya lagi.
Aku menggeleng.
"Aku enggak mau sok tahu Di. Apalagi menasehati takutnya malah menggurui." Jawabku.
"Menurutku hidup paling baik itu mengikuti alur Nti. Yang Maha Kuasa pasti sudah menyiapkan
takdir kita masing-masing. Kita tinggal menjalankan saja. Kamu itu kelahiran berapa Nti." Tanyanya.
"58. Kamu?" Tanyaku balik.
"52." Jawabnya.
"wah... enggak jauh beda ternyata." Jawabku.
"Apanya? Banyak itu jaraknya."
"masih tahun 50. Kita seangkatan ya."
"iya juga Nti."
Hari sudah semakin larut. Percakapan pun sepakat kami sudahi. Santo kembali ke rumahnya sementara
aku bergegas masuk untuk melanjutkan kegiatanku.
Tiba saatnya kurebahkan badanku yang sehari ini lelah oleh tugas-tugas dari Mas Sardi. Aku teringat
kata Santo tentang hidup yang dia jalani. Alangkah enaknya jika aku bisa seperti Santo. Hidup mengalir
saja tanpa tekanan. Sementara aku terus di bayangi tanggung jawab yang tak pernah cukup
memuaskan orang-orang di sekitarku. Hidup yang berubah drastis semenjak ayahku meninggal, kak
Mas Sardi mulai berubah, kak Mas Kardi menjadi hoby main kartu, dan Mas Mardi merantau ke Jakarta,
sementara adikku masih kecil.